 (Dok. Pribadi)
(Dok. Pribadi)
NODA gelap kembali mencoreng pesta demokrasi lokal. Kali ini terjadi di Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dua pasangan calon (paslon) yang berlaga pada pemilihan bupati di wilayah tersebut terungkap melakukan praktik politik uang. Satu suara dibeli oleh pihak paslon dengan harga sampai dengan Rp16 juta (Media Indonesia 17/5/2025). Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mendiskualifikasi kedua paslon dan memerintahkan pemungutan suara ulang dengan paslon yang baru.
Padahal, pilkada 22 Maret 2025 yang diperintahkan hanya berlangsung di dua tempat pemungutan suara (TPS) itu ialah pemungutan suara ulang (PSU) karena pada pilkada serentak 27 November 2024 lalu telah ditemukan bukti adanya penyalahgunaan hak pilih.
Berulangnya penyimpangan etika dan hukum dalam pilkada di daerah tersebut menjadi tamparan bagi proses demokrasi secara lokal atau secara khusus bagi daulat rakyat. Kebebalan politik dengan menempuh cara-cara kotor dan memalukan tersebut menjadi warisan kontestasi yang sangat riskan bagi nasib demokrasi lokal dan masa depan rakyat.
SELALU KANDAS
Eskalasi politik uang di berbagai daerah setiap ritual elektoral menumbuhkan kecemasan akan masa depan pembangunan demokrasi kita. Berbagai gerakan sosial dan moral yang bertajuk melawan politik uang sudah beribu kali dikumandangkan, aturan yang mencegah dan menegasi politik uang juga sudah tersedia, lengkap dengan sanksinya. Namun, semangat tersebut selalu kandas di ujung amplop fulus.
Sebenarnya, tak terbendungnya politik uang sudah disinyalkan oleh survei dari Lembaga Indikator Politik Indonesia yang mencatat pemilih yang memberikan suaranya karena uang meningkat pada Pemilu 2024. Terdapat 35% responden yang menentukan pilihan mereka karena uang pada Pemilu 2024. Lebih tinggi dari Pemilu 2019 (28%).
Pada Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan bahwa per November 2024, Bawaslu sedang melakukan kajian awal terhadap 130 kasus pelanggaran politik uang selama masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024. Terdapat dugaan pembagian uang atau materi lain di 7 provinsi dan 10 kabupaten/kota.
Sementara itu, dari laporan masyarakat, ditemukan dugaan pembagian uang atau materi lain di 7 provinsi dan 16 kabupaten/kota. Potensi pembagian uang atau materi lainnya ditemukan dari pengawasan Bawaslu di 3 provinsi dan 7 kabupaten/kota. Sementara itu, masyarakat melaporkan potensi pembagian uang dan materi lainnya di 12 provinsi dan 21 kabupaten/kota.
Sepertinya normalisasi politik uang kian membelukar dan mencengkeram daulat rakyat. Uang haram dalam transaksi politik menjadi komoditas yang digerakkan untuk menggiring masyarakat ke dalam jebakan permisivitas 'wani piro' (berapa yang berani kamu tawarkan) dan menganggap uang yang digelontorkan oleh para politisi ialah 'hak' masyarakat yang telah berlelah-lelah ke TPS.
Sementara itu, bagi politisi, uang suap kepada rakyat adalah bagian dari 'sikap baiknya' kepada rakyat di tengah pesta yang hanya sekali lima tahun terjadi. Para elite memang berada di titik banal kerakusan terhadap kekuasaan sehingga gemar memproduksi berbagai metode manipulatif dan penuh kelicikan di tiap proses pilkada. Mereka selalu membaca kekuasaan dalam gairah onani yang mereduksi makna suara rakyat hanya dengan kepuasan fulus dan kursi kekuasaan.
PLUTOKRASI
Kevin Phillips dalam Wealth and Democracy: a Political History of the American Rich (2002) mengatakan bahwa praktik demokrasi mulai tersandera oleh budaya plutokrasi (ploutos: kekayaan dan kratos: kekuasaan) yang menjadikan uang sebagai episentrum dari 'habitus' demokrasi.
Cengkeraman plutokrasi tersebut tanpa sadar telah lama mendegradasikan makna politik kita, dari sebuah arena perwujudan kepentingan bersama menjadi panggung pengultusan uang dan kekayaan yang difasilitasi politik berbiaya tinggi, untuk meraih kemenangan politik. Maka itu, tidak heran jika di lembaga legislatif atau eksekutif sebagai institusi penting untuk memproduksi kebijakan publik, selalu dihuni oleh politisi yang berlatar orang-orang kaya sekaligus menahbiskan bahwa dunia politik hanya milik politisi berkantong tebal.
Padahal, filsuf Plato (427 SM-347 SM) menegaskan bahwa untuk mengelola negara, dibutuhkan orang-orang yang bijaksana dan cerdas, bukan yang hanya memiliki akses kapital. Dalam perspektif demokrasi, contohnya, nilai moral dan etika selalu menjadi ruh yang diproyeksikan oleh masyarakat demokratis untuk menegakkan prinsip kemaslahatan bersama (bonum commune) dalam tata kelola bernegara.
Sayangnya, prinsip tersebut belum menjadi orientasi dalam cara berdemokrasi sampai detik ini. Upaya mencapai kekuasaan (materialisme) dengan menghalalkan segala cara pun selalu mendapatkan ruang justifikasi di berbagai agenda suksesi. Nilai subtansi berdemokrasi (integritas, moralitas, transparansi, dan akuntabilitas) begitu gampang dikangkangi oleh hal-hal prosedural yang dibungkus berbagai rekayasa dan tipu daya.
Dalam kontestasi elektoral, praktik demokrasi kerap dimaknai sebatas prosedural: ritual kampanye, pemungutan suara. Namun, melupakan prinsip substantif: otonomi, kebebasan politik, kesetaraan, toleransi, dan tanggung jawab, termasuk aturan main (rule of the game) politik yang berbasis supremasi hukum dan kontrol sipil.
Padahal, pada pemenuhan prinsip substantif itulah tersimpan kebajikan yang menebalkan makna esensial berdemokrasi. Di situlah rakyat menemukan kedaulatannya sebagai warga negara (citizenship) karena memiliki kesadaran kewarganegaraan (sense of citizenship) dalam menjaga hak daulatnya.
Ke depan, penanaman sense of citizenship dalam diri rakyat adalah mutlak. Bahwa dalam diri masyarakat ada tanggung jawab menyelamatkan kedaulatannya dari 'kutuk' politik uang. Agar demokrasi kembali dimaknai sebagai one man one vote, bukan one man one million yang mereduksi martabat rakyat.
Maka itu, tak cukup dengan undang-undang antipolitik uang ataupun penegakan hukum. Pendidikan politik sangat diperlukan untuk memupuk kesadaran dan kedewasaan bernegara dari masyarakat. Negara harus memfasilitasi internalisasi nilai tanggung jawab politik tersebut dalam konteks pembangunan demos yang kontinu dan investatif, ketimbang misalnya memboroskan 'bagi-bagi bansos (bantuan sosial)' yang justru makin mengentalkan ketidaksetaraan rakyat dan elite atau negara.
Negara, termasuk parpol, harus serius menginvestasikan nilai edukasi politk bagi rakyat agar politik uang, korupsi, plutokrasi di bangsa ini bisa dikalahkan sengatnya, digantikan dengan perilaku politik elite dan rakyat yang bermartabat.

 7 hours ago
2
7 hours ago
2













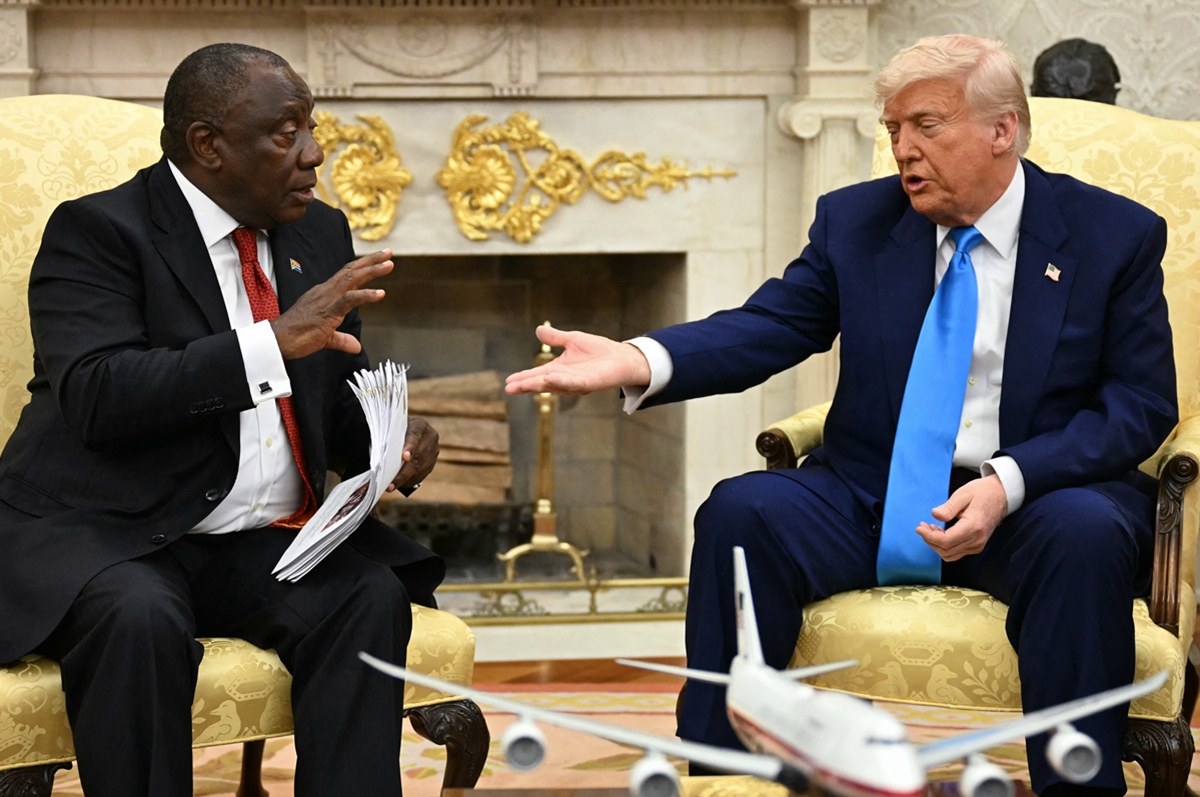






:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5057505/original/086000600_1734592256-IMG-20241219-WA0069.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4481713/original/052265400_1687776262-dima-solomin-mr26tQgHGmc-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5135961/original/076587700_1739804548-20250217BL_Kedatangan_Tim_Bulu_Tangkis_Indonesia_setelah_Menjuarai_BAMTC_2025_2.JPG)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2239191/original/052979500_1528188241-Timnas_Indonesia_Hindia_Belanda.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5135093/original/045886300_1739723206-FOTO_BERITA.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5124728/original/023615200_1738900872-jude-bellingham-rodr_5837f0d.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4291039/original/040611000_1673668425-FmSR6W0WAAIwh1l.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4007916/original/000502300_1651022535-4.JPG)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5126293/original/095807200_1739054781-000_36XG3AL.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5084263/original/096728200_1736318753-GN87b-UW0AAdire.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/4955392/original/000378200_1727509805-20240927BL_Timnas_Indonesia_U-20_Vs_Timor_Leste_di_Kualifikasi_Piala_Asia_U-20_2025_25.JPG)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5132884/original/072355000_1739511640-900x900.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5129832/original/009209800_1739306237-CITY_MADRID_1.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4662973/original/038204500_1700891152-Apple-iPhone-SE-4-concept-render-1024x576.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4147879/original/003303700_1662436165-cek_bansos.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5128340/original/042681100_1739243370-nfs-11-feb-2025-d7bb8c.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1188431/original/004450900_1459423620-517979832.jpg)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5135707/original/002195800_1739783758-Tekel_Horor_Rizky_Ridho_Beckham_Putra-6.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5128403/original/082340700_1739246271-000_34TP9FQ.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5143666/original/028852800_1740548429-Cinta_di_Ujung_Sajadah_0.jpeg)